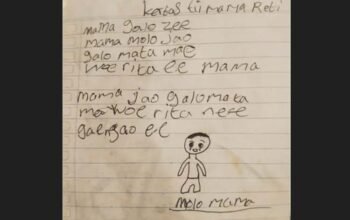AKHIRNYA ujung yang di cari manusia itu satu saja: bahagia. Manusia ingin berada dalam kebahagiaan. Atau manusia selalu ingin terjaga dalam kebahagiaan, disetiap waktunya dan disepanjang hidupnya.
Bahagia itu, kalau bisa: ‘di sini’. ‘Saat ini’.
Tapi bahagia tak selalu bisa di ‘pegang’. Ia seperti balon udara yang terbang melayang-layang. Sering keberadaanya makin bergerak menjauh dan sulit di rengkuh.
Orang modern berkepercayaan, bahagia itu dengan cara ‘memiliki’. Hebat itu ‘memiliki banyak’. Wah dan wow itu ‘memiliki berkelebihan’. Gagah dan sukses itu ada bandrol ‘milik’ yang melekat pada diri.
Bandrol itu simbol berapa banyak ‘milik’ manusia. Siapa anda, adalah berapa nilai bandrol yang melekat pada diri anda, pada kemeja anda, pada kaca mata anda, pada sepatu anda, pada sepada anda, pada mobil anda, pada rumah anda, pada minyak wangi anda, pada jabatan dan kedudukan anda, bahkan pada cara potong rambut anda.
Bandrol, simbol milik, adalah eksistensi. Anda ‘ada’, atau merasa ‘ada’, bergantung bandrol anda. Anda tak ‘memiliki’, atau anda tak berbandrol, maka anda ‘tak ada’ atau merasa ‘tak ada’.
Apa yang membedakan anda dan lainya adalah nilai bandrol anda. Termasuk bahagia dan derita bergantung bandrol yang anda miliki.
Itulah rezim modern yang kukuh mengusai peradaban hari ini. Keberadaannya telah menjadi nafas kebudayaan, menjadi elan pembangunan, menjadi spirit pendidikan serta meresap dalam hingga kehidupan keluarga dan menancap kuat pada pribadi-pribadi.
Bisa dipahami, jika dinamika modern menciptakan masyarakat konsumerisme. Manusia dipacu berlomba untuk ‘mengumpulkan’ dan ‘memiliki’. Seluruh waktunya boleh dibilang untuk mengejar ‘jumlah’ dan ‘status’ kepemilikan.
Akankah peradaban modern mencapai pada puncak tujuan kehidupan manusia: kebahagiaan?
Tak akan! Mustahil! Mungkin itu kira-kira yang akan diucap Erich Fromm, salah seorang tokoh psikologi humanistik. Mengejar kebahagian dengan cara ‘memiliki’, ‘mengumpulkan’ melalui gaya hidup konsumerisme (to have) sebetapapun banyaknya itu fatamorgana. Menipu. Kebahagiaan itu bukan diperoleh dari ‘luar’. Melainkan kekuatan dari ‘dalam’ diri manusia (inner). Salah satu unsur penting kekuatan dalam itu adalah cinta.
Namun cinta yang dimaksud bukanlah cinta Freudian yang sifatnya seksualitas. Karena cinta seperti ini masih tergolong kebutuhan fisik (fisiologis) jika ditilik dari kebutuhan dasar Maslow.
Cinta yang dimaksud seperti digambarkan Carl Rogers (psikolog humanistik), yakni perasaan mendalam saling mengerti dan memiliki sepenuh hati antar sesama manusia. Cinta seperti ini adalah kebutuhan pokok manusia yang bukan material sifatnya. Kehilangan hubungan cinta ini dipastikan manusia mengalami gangguan jiwa (neurosis). Manusia menjadi tak utuh. Ada sisi hilang yang membuat kebahagiaan itu tak mungkin tercapai. Ketakutuhan itu membuat manusia ‘kesunyian’. Ada rasa “keterasingan’ atau alienasi kata Fromm meminjam istilah dari Karl Marx.
Oleh karena itu, manusia modern adalah tipe manusia sakit, karena ia kehilang dimensi cinta dalam kehidupannya. Corak individualistisnya yang teramat kuat membuat manusia modern kehilangan ikatan-ikatan cinta mendalam antar sesama.
Pada cinta yang muncul dari dalam (inner), rasa ‘berarti’ seperti kata Fromm, justru pada kehendak ‘memberi’. Bukan ‘mengambil’ atau ‘memiliki’. Memberi itu termanifestasi pada dedikasi, totalitas, produktifitas, ‘memberi yang terbaik’, berkarya, beremphati, hubungan kehangatan, suasana keguyuban dll.
Mekarnya cinta dari ‘dalam’ ini membuat manusia ‘menjadi’ (to be). Ia merasa ‘ada’, ‘tumbuh’ dan eksis. Manusia ‘ada’, sebagaimana kata Viktor Frankl (Logo therapy), karena ia merasa ‘bermakna’. Kebahagiaan selalu berada dalam atmosfir makna. Bahagia pada posisi ini bukan sesuatu yang berjarak, apalagi dikejauhan. Dalam kehidupan bermakna, disitulah letak ‘ada’ dan bahagia menyatu. [rif]