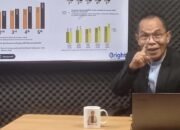BEBERAPA tahun setelah Indonesia mulai banyak berutang tadi, kondisi keuangan dunia ditandai fenomena kelebihan likuiditas. Berbagai lembaga keuangan internasional memiliki banyak dana terutama karena fenomena petro dollar. Fenomena akibat kenaikan harga minyak sejak awal 70-an, yang sangat signifikan.
Selain disimpan pada berbagai bank dan lembaga keuangan komersial, dana dari negara-negara produsen minyak tersebut juga berpengaruh pada lembaga seperti International Monetary Fund (IMF). IMF bisa memainkan peran sebagai perantara keuangan yang memperoleh keuntungan. Dalam bahasa awam, IMF bisa kulakan dana murah kemudian disalurkan ke banyak negara.
Rezeki minyak itu sebenarnya secara langsung juga diperoleh oleh Indonesia, terhitung sejak tahun 1974. Produksi minyak Indonesia masih jauh melebihi kebutuhan konsumsinya, sehingga bisa net ekspor. Dengan harga yang melambung tinggi itu, cadangan devisa menjadi sangat besar.
Lantas, apakah dengan rezeki yang berlimpah dan cadangan devisa yang banyak itu, Indonesia berhenti mencari utangan baru? Ternyata, tidak demikian. Utang luar negeri makin meningkat.
Narasi kebutuhan utang yang kemudian bergeser. Bukan lagi karena Indonesia miskin, kekurangan devisa untuk impor kebutuhan penting rakyat. Juga bukan semata untuk memperbaiki kapasitas produksi perekonomian nasional. Melainkan, soal momentum berkembang menjadi negara maju, karena telah memiliki modal sendiri.
Dikembangkan analisis bahwa meski telah memiliki modal, namun masih belum mencukupi untuk menjadi kaya. Masih memerlukan tambahan modal asing dan utang luar negeri.
Pihak pemberi utang pun makin bergairah. Indonesia dianggap akan mampu bayar utang, antara lain karena memiliki sumber penerimaan minyak. Syarat dan bunga pun mulai menyesuaikan. Lebih menguntungkan bagi kreditur, dan mulai memberatkan Indonesia.
Pihak Indonesia (pemerintahan Soeharto) sebagai orang kaya baru (OKB) tampak tidak keberatan. OKB ini mulai memperbaiki narasi mimpinya. Bahkan melalui dokumen resmi kenegaraan, seperti GBHN dan Repelita. Soeharto mencanangkan keinginan menjadi kaya betulan dan berkelanjutan. Indonesia diyakini akan lepas landas, menuju negara maju dan seluruh rakyatnya keberlimpahan konsumsi.
Tidak hanya pemerintah, kelompok pengusaha Indonesia yang mulai tumbuh kembang pun memiliki mimpi serupa. Mereka ingin menjadi kaya raya dan usahanya nanti masuk ke pasaran global sebagai pemain penting. Narasinya kembali pada kebutuhan modal tambahan, karena keuntungan selama ini masih belum mencukup mewujudkan mimpi sebesar itu.