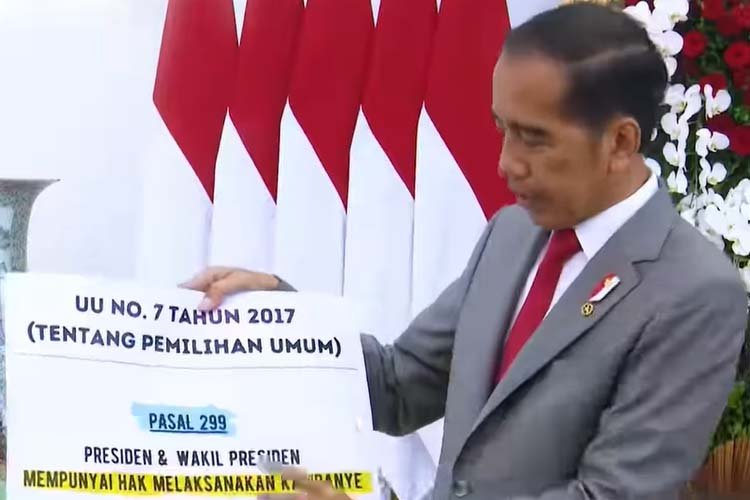PEMILIHAN Presiden masih delapan bulan lagi. Presiden lama masih menjabat dan calon-calon presiden masa depan sudah bersiap.
Jokowi sebagai petugas partai eh presiden tentu saja paling sibuk. Mengalahkan para ketua umum partai politik. Di beberapa kesempatan ia malah merasa harus mengendorse calon-calon yang menurutnya layak.
Salahkah?
Tentu saja tidak. Sebagai kepala negara yang bertanggungjawab, ia punya kepentingan mengamankan hal-hal yang menguntungkan para penyokong dana dan elite parpol rakyat Indonesia. Ia ingin jadi presiden yang luar biasa. Nggak kayak Pak Harto yang bahkan bersedia mundur saja tetap memikirkan keutuhan negara dan ketenangan rakyatnya. Atau Gus Dur yang bahkan tak terbukti bersalah tetap bersedia meletakkan jabatan agar tak ada bentrokan antarwarga.
Jokowi ingin melebihi mereka, ia menempatkan pemilik modal alias oligarki yang selama ini mendiktenya rakyat sebagai subyek yang harus disejahterakan. Jadi ia merasa perlu cawe-cawe.
“Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden, tapi juga saya titip pesen jangan terlalu lama-lama,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara HUT ke-58 Golkar digelar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Masih belum yakin dengan pesannya, maka ia mengulang-ulang lagi pesannya bahkan akhirnya memutuskan untuk cawe-cawe agar orang-orangnya dari pemilik modal sampai penyokong yang menikmati uang negara rakyat terjamin hidupnya selamanya.
Jika pemilu presiden sebelumnya nyaris tidak menimbulkan riak berkepanjangan, khusus pilpres 2019 ternyata masih menyimpan bara dendam di level akar rumput.
Bara ini harus dijaga agar tetap menyala sehingga rakyat Indonesia punya alasan menggelar silaturahmi, rekonsiliasi atau apapun namanya yang melibatkan elite parpol dan ada kucuran uang negara. Jadi bara dendam itu harus ada agar rakyat kebagian uang saku mengikuti pertemuan-pertemuan yang digelar banyak pihak.
Sejatinya konflik dan persaingan, dalam kadar tertentu, adalah konsekuensi dari hidup bermasyarakat. Setiap hari masyarakat dihadapkan pada konflik: kepentingan sosial, ekonomi maupun budaya. Tiap kelompok punya kepentingan yang berbeda dari kelompok lain.
Perbedaan itu niscaya bahkan jika kita bersumpah “satu Indonesia”. Itu juga niscaya bahkan jika orang Islam terobsesi dengan “satu Islam”, misalnya.
Demokrasi menjadi sarana untuk membuat persaingan kepentingan menjadi lebih beradab, bukan menghilangkan persaingan dan perbedaan. Bandingkan dengan jika kita harus menyelesaikan perbedaan lewat otot, pedang atau bedil.
Idealnya begitu. Tapi bagi Jokowi, mengelola persaingan dan perbedaan itu nggak efisien. Nggak bisa menjalankan slogan kerja, kerja, kerja, thypus.
Peran lembaga survei juga tak lagi mengukur etikabilitas tapi justru popularitas sebagai parameter elektabilitas. Ini juga menguntungkan karena kemudian membuka lapangan kerja bagi pengangguran yang hobi bersilat lidah menjadi buzzer.
Pemilihan umum dan demokrasi berubah menjadi politainment, politik entertainment. Yang namanya entertainment tentu saja banyak drama dan hiburannya. Ini penting bagi rakyat yang setiap gerakannya sudah diintai pajak. Setidaknya bisa untuk hiburan.