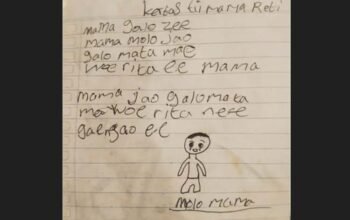Oleh: Achmad Fachrudin, Akademisi dari Universitas PTIQ Jakarta
TERMINOLOGI kartel lajim digunakan untuk menunjuk praktik persekongkolan sejumlah perusahaan (bisnis) dalam mengendalikan jumlah produksi, harga atau jasa untuk beroleh keuntungan tidak wajar. Kemudian oleh sejumlah sarjana politik, seperti Ambardi (2008), Slater (2014), Muhtadi (2015) untuk menyebut sejumlah nama, istilah kartel digunakan untuk memotret persekongkolan politik antar partai politik (Parpol), elit politik maupun dengan penguasa untuk memenangkan kontestasi elektoral dengan cara yang tdak wajar. Bahkan menjurus curang.
Sebenarnya politik kartel sudah diterapkan di masa regim Orde dengan Soeharto sebagai presiden dan Golkar sebagai operator politik serta Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud kala itu sebagai bolduser politiknya. Hanya saja pola atau modusnya tidak dalam persekutuan besar dan banyak melibatkan partai politik (Parpol) karena jumlah Parpol hanya tiga, yakni: Partai Perstuan Pembangunan atau PPP, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dalam mengoperasikan politik kartel di masa orde baru, lebih banyak melibatkan antara Golkar, birokrasi, militer dan pebisnis, khususnya yang beraliansi (kroni) dengan keluarga Cendana.
Sebagaimana diungkap Indonesianis asal Amerika Serikat Jeffrey Alan Winters, tumbangnya regim orde baru dan lahirnya regim reformasi tidak serta merta membuat praktik kartel politik atau tepatnya oligarki politik lenyap, melainkan tetap eksis dan survive dengan katalisator dan aktor-aktor politiknya mengalami deferensiasi. Sementara Golkar, tidak lagi menjadi partai penguasa (the ruling party) di masa reformasi. Kecuali pada 2004 karena menang dalam Pemilu saat itu. Namun dengan modalitas sumber daya manusia, dan pengalaman panjang sebagai partai penguasa, Golkar masih tetap memainkan peran strategis. Bahkan dalam beberapa peristiwa politik krusial, elit Golkar mampu menjadi lokomotif politik.
Dimensi Historisitas
Kuskrido Ambardi dalam buku bertajuk “Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi” membedah, sejak reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Ambardi lalu menyebut, lima ciri kartel dalam sistem kepartaian, yaitu, (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai, (2) sikap permisif dalam pembentukkan koalisi, 3) tidak adanya oposisi, (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ciri ini, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.
Katz dan Mair (1995) mengamati, partai kartel yang muncul paska tahun 1970, dianggap sebagai model baru karena bukan hanya menggunakan capital intensive dalam strategi kampanye tetapi juga menjadikan Parpol sebagai profesi individu. Lebih dari itu, menggunakan negara sebagai sumber daya pendanaan partai. Konsekwensinya Parpol menjadi lebih dekat dan tergantung dengan negara atau penguasa daripada dengan masyarakat. Di masa reformasi, makin lumrah terjadi Parpol menghianati aspirasi pendukungnya dan memilih mendekat kepada penguasa.
Slater (2004) mengamati, pasca-Pemilu 1999 politik kartel justeru menunjukkan makin menguat. Perbedaan dan preferensi ideologi partai yang sempat mencuat pada awal maraknya lahir Parpol baru plus tiga Parpol lawas (PPP. Golkar, dan PDI yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan), secara lambat namun pasti akhirnya pupus. Disini, ungkap Slater dan Ambardi, kolaborasi antar partai, antar partai dan dengan pemerintah, bukan untuk berkompetisi secara demokratis dan sehat, melainkan untuk mengambil keuntungan secara curang.
Dalam situasi ini, tulis Rendy Pahrun Wadipalapa, (Kompas, 10 Mei 2022), Pemilu bukan lagi manifestasi penghormatan atas suara rakyat, melainkan satu periode yang membuka seluas-luasnya bazar kompromi, mengatur ulang posisi kekuatan politik masing-masing. Kartel, dalam pengertian ini, adalah jejaring kolusif yang disatukan oleh kesamaan kepentingan dan selalu berjalan di atas negosiasi, kompromi, dan kooptasi antarkelompok.
Jokowi Effect
Sebenarnya kemunculan dan sekaligus kemenangan Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, diharapkan membawa angin bagi perubahan demokrasi dan budaya politik secara mendasar, dengan salah satunya memberangus politik kartel hingga keakar-akarnya. Namun apa lacur, harapan tersebut sirna ketika akhirnya Jokowi juga menerapkan politik kartel dengan memasukkan Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, masuknya Golkar dan PAN di pemerintahan bisa menjebak presiden dalam kartel politik. Padahal Presiden Jokowi sudah mendapat dukungan dua pertiga kursi di parlemen. Langkah Presiden Jokowi tersebut, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, bisa mengurangi check and balance pemerintah di parlemen.
Menjelang Pilpres 2019, seperti ditulis Bahtiar dan kawan-kawan (Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI, Agustus 2022), penguasa melakukan tranformasi dari partai massa yakni: repsentative capacity. Namun faktanya, rekayasa elektoral pada Pemilu Serentak 2019 tersebut tidak mampu meningkatkan representasi politik. Begitupun dengan tujuan partai catch-all adalah efektivitas kebijakan. Sejauh ini, janji kampanye seringkali tidak menjadi prioritas utama ketika menjabat. Program kerja dibuat untuk memenangkan pemilu, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, rekayasa elektoral pada Pemilu 2019 berdampak pada menguatnya Parpol kartel.
Sementara menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi pada Oktober 2024, indikasi terus menguatnya politik kartel makin menghawatirkan. Bahkan bersimbiosis-mutualistik dengan menguatnya politik dinasti yang melibatkan anak-anak dan menantu presiden Jokowi. Tanpa menafikan legasi (warisan) berharga dan bernilai yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. sejumlah catatan kritis dan buruk perlu dialamatkan kepada regim. Sehingga Majalah Tempo edisi khusus 10 tahunnya, memplesetkan Nawacita Jokowi menjadi Nawadosa Jokowi. Hal ini bisa dikatakan tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Presiden Jokowi (Jokowi effect).
Kesepuluh Nawadosa Jokowi tersebut, sebagai berikut: Pertama, dinasti dan oligarki politik. Kedua, pelemahan insitusi demokrasi. Ketiga, keterlibatan TNI di ranah sipil. Keempat, konflik Papua tak kunjung padam. Kelima, runtuhnya sistem Pendidikan. Keenam, watak patron-kelian kepolisian. Ketujuh, politisasi kejaksaan. Kedelapan, pelemahan KPK. Kesembilan, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat.
Kemudian kesembilan, karut marut mengelola APBN. Kesepuluh, karut marut mengelola APBN. Kesebelas, runtuhnya independensi Bank Indonesia. Keduabelas, ketergantungan utang Cina. Ketigabelas, pemaksaan ibukota negara. Keempatbelas, gimik demokrasi luar negeri. Kelimabelas, kerusakan lingkungan. Keenambelas, konflik agraria. Ketujuhbelas, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Kedelapan belas, kebebasan sipil yang menyempit,
Paska Pilpres 2024 berakhir dengan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto menjadi peraih suara terbanyak dengan mengalahkan Paslon Capres Anies Rasyid Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Capres Prabowo mengusung isu atau narasi kesinambungan, Sedangkan Capres Anies mengusung tema perubahan. Jika kesinambungan dimaknai secara dinamis dan selektif dalam arti melanjutkan yang baik dan positf lalu membuang yang negatif dari kepemimpinan dan pemerintahan Jokowi, itulah yang didambakan oleh rakyat kebanyakan terlepas pilihan politiknya saat Pilpres 2024. Masalahnya akan menjadi ancaman dan bahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di bidang pembanguann demokrasi, manakala presiden terpilih Prabowo melanjutkan dan apalagi memperkuat warisan buruk. Salah satunya adalah politik kartel.
Dinamika Politik Kartel
Pendiri Saiful Mujani Research and Consultan (SMRC) Prof. Saiful Mujani melihat tanda-tanda Pilgub DKI Jakarta dan Pilkada Serentak di sejumlah deerah di Indonesia diwarnai berbagai tekanan koalisi pemenang Pilpres 2024. Tekanan koalisi ini terlihat dari sejumlah indikasi seperti perubahan sikap dan dukungan partai-partai kepada kandidat-kandidat yang akan berlaga di Pilgub Jakarta.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, sebelumnya telah mendeklarasikan Pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswedan dan Sohibul Iman (AMAN). Belakangan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengumumkan hasil Musyawarah Dewan Syura PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (10/8/2024) justeru menyatakan, telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut sekaligus sebagai isyarat atau sinyal PKS meninggalkan Anies dan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Bahkan kemungkinan besar PKS masuk pada kabinet Prabowo mendatang. Sebelumnya sejumlah politisi PKS berdalih, Cagub DKI Anies telah diberikan tenggat waktu 40 hari hingga 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan di Pilgub DKI Jakarta. Ini pernyataan aneh bin Ajaib. Sebab, Anies hanya Cagub DKI. Sementara yang mempunyai kekuatan politik tawar menawar kuat ke Parpol lain adalah Pimpinan PKS.
Sampai deadline pengusulan nama Cawagub DKI, Anies dianggap tidak mampu melakukan pendekatan dengan Parpol lain. Dengan alasan itu pula, PKS melirik dan ‘main mata’ dengan poros KIM dan bertandang ke presiden terpilih Prabowo. Dengan alasan berbeda namun tujuannya beririsan, tampaknya dilakukan oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan membelot ke KIM sehingga muncul KIM-Plus.
Jika PKS bergabung dengan KIM Plus, berdampak Koalisi Perubahan (KP) malah menjadi KP-Minus, serta cerai berai. Secara otomatis Anies ditinggal sendirian begitu saja. Tinggal PDI Perjuangan yang memiliki 15 kursi. Hanya saja jika ingin mencalonkan Anies atau mencalonkan Cagub DKI sendiri, PDI Perjuangan harus bergabung dengan Parpol lain untuk dapat menggenapi 22 kursi di DPRD DKI sebagai syarat Parpol atau gabungan Parpol dapat mengajukan Cagub dan Cawagub DKI di Pilgub DKI 2024. Tentu ini bukan hal yang mudah.
Jika semua tiket Cagub DKI diborong oleh KIM Plus menjadi kenyataan, opsinya tinggal dua, yakni: Pertama, Ridwan Kamil (RK) yang digadang-gadang Cagub DKI dari KIM Plus tidak akan mendapat lawan Cagub DKI Anies karena sudah ditinggalkan oleh PKS maupun Koalisi Perubahan. Sedangkan Cagub DKI dari PDI Perjuangan karena juga mengalami kekurangan dukungan politik untuk dapat mengajukan Cagub DKI dan Cawagub DKI di Pilgub DKI 2024 berada pada posisi kritis dan penuh ketidakpastian.
Opsi kedua, RK akan berkontestasi melawan calon perseorangan, yakni: Dharma Pongrekun yang berpasangan dengan Kun Wardana Abyoto (Dharma-Kun). Dengan catatan, pasangan Dharma-Kun lolos dari verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) lalu ditetapkan oleh KPU DKI menjadi Cagub DKI dari perseorangan. Jika tidak lolos vermin dan verfak, maka RK berpotensi melawan kotak kosong.
Kerja-kerja politik kartel membangun skenario sistematis semacam ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa desain dan rekayasa politik canggih. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh suatu kekuatan besar (powerful) yang biasa disebut dengan oligarki. Pengalaman pada sejumlah negara, oligarki itu sesungguhnya bisa dijinakkan, ditaklukan dan dikendalikan. Syaratnya antara lain tersedianya dukungan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang kuat, solid dan bersatu. Masalahnya sejak beberapa Pemilu atau Pilkada terakhir, kekuatan OMS di Indonesia cenderung lemah, rapuh dan terfragmentasi. Karenanya saat ini sulit diharapkan menjadi lokomotif gerakan demokratisasi yang efektif. Apalagi harus melawan kartel politik atau oligarki politik.
Catatan Reflektif
Tanpa bermaksud mengecilkan peluang Dharma-Kun atau bisa saja terjadi kejutan politik dimana PKS dengan Koalisi Perubahan kembali on the track dengan cara mengusung Anies sebagai Cagub DKI. Skenario lain, PDI Perjuangan dengan mitra koalisinya mampu mengusung Basuki Tjahaja Purna (Ahok) menjadi Cagub DKI. Bahkan tidak tertutup kemungkinkan pula PDI Perjuangan mengusung Anies sebagai Cagub DKI sebagai pembuktian sebagai partai perjuangan sejati.
Muaranya pada Pilgub DKI 2024 mampu mengontestasikan antara RK dengan Anies atau RK dengan Ahok. Jika ini terjadi, kompetisi di Pilgub DKI akan seimbang dan menarik. Dan kepercayaan publik terhadap Pilgub DKI kembali normal setelah dalam beberapa hari terakhir dibombardir dengan rekayasa wacana maupun aksi yang mengarah kepada pelemahan demokrasi di Jakarta. Namun sekaligus akan menjadi tamparan keras bagi poros KIM plus karena dianggap tidak sanggup mengamputasi Anies dalam belantika Cagub DKI.
Manakala RK tidak melawan Anies atau Ahok dan hanya berkontestasi melawan calon perseorangan atau bahkan kotak kosong, diatas kertas RK yang disokong koalisi KIM Plus serta kekuatan politik kartel lainnya akan dengan mudah melenggang ke Balaikota Jakarta. Bukan tak mungkin di Pilgub DKI akan bertanding seperti antara David dengan Goliat. Skenario sistematis semacam ini hanya dapat dilakukan jika adanya tangan-tangan kekuasaan (hand of power) atau politik kartel yang melibatkan kekuatan politik lama yang akan berakhir (Presiden Jokowi) maupun kekuatan politik baru (Prabowo).
Jika dampak politik kartel di Pilgub DKI 2024 tidak mampu dicegah atau dikendalikan, ada beberapa kemungkinan dampak negatif yang patut direfleksikan. Yakni: pertama, mengancam budaya demokrasi di Jakarta yang sudah dibangun sejak susah payah sejak Pilgub DKI 2007, 2012, 2017 dan 2022. Kedua, kontestasi politik menjadi tidak menarik karena tidak berimbang. Ketiga, komodifikasi politik bakal makin merajalela. Keempat, berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Kelima, paling dikuatirkan Pilgub DKI 2024 mengalami demoralisasi dan delegitimasi terhadap Penyelenggara dan peserta Pilgub DKI maupun terhadap proses maupun hasil Pilgub DKI 2024. [r]