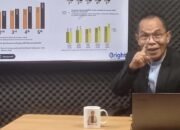POSISI utang pemerintah era pemerintahan Habibie memang tercatat sangat besar, bertambah amat sigifikan dibanding akhir era Soeharto. Tidak hanya berupa utang luar negeri, melainkan bertambah dengan utang dalam negeri.
Namun mesti diketahui bahwa hal itu disebabkan warisan kondisi dan kebijakan era Soeharto. Terutama untuk membiayai penanganan krisis ekonomi, krisis moneter, dan krisis perbankan.
Dampak kondisi dan kebijakan era Soeharto bahkan masih berlanjut pada era pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Posisi utang pemerintah masih terus bertambah secara cukup signifikan.
Pengertian posisi utang dalam kehidupan sehari-hari adalah sisa utang yang mesti dilunasi. Ada dua cara menyajikan posisi utang pemerintah itu, yaitu dalam nilai rupiah atau dolar amerika. Utangnya sendiri pada era ini memang ada yang berdenominasi rupiah, berupa surat utang atau obligasi. Ada yang berupa berbagai mata uang asing, sebagai kelanjutan ULN lama ditambah utang pada International Monetary Fund (IMF).
Dalam catatan nilai rupiah, posisi utang sebesar Rp238 trilyun pada akhir tahun 1997, dan menjadi Rp940 triliun akhir tahun 1999. Dengan demikian bertambah 395% atau menjadi hampir empat kali lipat selama dua tahun.
Peningkatan tidak sedrastis itu jika dilihat dalam nilai dolar Amerika. Antara lain karena pelemahan nilai kurs rupiah yang mengakibatkan catatan posisi utang dalam nilai rupiah terdongkrak. Dilihat dalam nilai dolar, kenaikan “hanya” sebesar 246% atau dua setengah kali lipat. Dari US$53,87 milyar (akhir 1997) menjadi US$132,39 miliar (akhir 1999).
Pada era Gus Dur dan Megawati, utang pemerintah dalam catatan nilai rupiah bertambah sebesar 38,3% menjadi Rp1.300 trilyun (akhir 2004). Sedangkan dalam nilai dolar Amerika hanya bertambah 5,66 %, menjadi US$139,88 milyar (akhir 2004).
Masalah utama dari utang pemerintah bukan lah besarnya sisa utang. Melainkan beban pembayaran dalam pelunasan utang pokok dan biaya bunganya. Pembayaran bunga utang selama era Habibie, Gus Dur dan Megawati mulai meningkat pesat dan makin membebani keuangan pemerintah.
Biaya utang pada era Soeharto, terutama pada dekade akhir pemerintahan, sebenarnya juga telah cukup besar. Namun karena berupa pinjaman luar negeri, maka biaya yang tinggi agak tersamarkan. Sebagian besar bentuk utang berupa “barang dan jasa” yang diberi harga oleh kreditur. Mereka tentu saja telah mengambil margin keuntungan dari aspek itu. Biaya dalam bentuk pembayaran bunga utang pun dapat ditekan rendah.
Ketika utang dalam negeri yang berbentuk surat utang naik berkali lipat, maka pembayaran bunga pun meningkat. Pembayaran beban bunga tersebut langsung tercatat pada anggaran pemerintah.
Dalam hal pelunasan pokok utang, beban utang juga makin terasa memberatkan seiring dengan jatuh temponya sebagian utang yang ditarik pada era Soeharto. Pelunasan tidak mungkin bersumber dari pendapatan, karena untuk belanja pun tidak mencukupi. Pilihan yang tersedia adalah menjual aset dan privatisasi (saham) perusahaan milik negara, serta berutang lagi.
Pada era Gus Dur dan Megawati, Pemerintah masih memiliki banyak aset yang berasal dari program restrukturisasi perbankan. Perbankan peserta program BLBI dan restrukturisasi ditalangi utang dan kewajibannya, namun diambil alih aset-aset hingga kepemilikan perusahaan. Tanah dan bangunan termasuk dalam jenis aset dimaksud.
Sederhananya, Pemerintah dengan bantuan Bank Indonesia mengambil alih sebagian besar utang dan aset perbankan. Akibat hal ini, utang pemerintah membengkak, namun memiliki banyak aset dan saham kepemilikan. Sayangnya, setelah bertahun-tahun kemudian baru diketahui secara pasti bahwa nilai sitaan jauh lebih rendah dari dana yang bersumber dari utang pemerintah.
Bagaimanapun, nilai yang bisa dijual dan diprivatisasi masih cukup besar. Prosesnya berlangsung selama bertahun-tahun. Penjualan aset terbesar dilakukan pada era Gus Dur dan Megawati. Secara lebih khusus, era Megawati yang terbesar dalam menerima hasil privatisasi.
Meski demikian, penerimaan pemerintah masih belum mencukupi untuk menutupi pengeluarannya. Harus diingat, pengeluaran dimaksud mencakup belanja dan membayar pelunasan pokok utang.
Akibatnya upaya berutang atau penarikan utang baru tetap dilakukan. Pada era Gus Dur belum mengandalkan cara berutang dengan penerbitan surat utang, hanya dari penarikan pinjaman luar negeri. Pada era Megawati, kedua cara berutang dilakukan.
Salah satu yang menarik adalah fenomena hubungan IMF dan Indonesia pada era pemerintahan Gus Dur yang tampak memburuk. IMF menunda pencairan dana utang akibat belum tuntasnya revisi sejumlah Undang-Undang. Diantaranya tentang bank sentral, otonomi daerah, serta revisi APBN 2001.
Dari lima bagian tulisan yang telah dikisahkan, beberapa hal bisa dikatakan dalam bahasa awam tentang fenomena utang pemerintah Indonesia. Pada era Soekarno, terpaksan berutang karena kesulitan pangan dan infrastruktur. Pada era Soeharto, mulai membangun secara besar-besaran, terus berutang. Masih pada era Soeharto, ketika sempat cukup kaya karena rezeki minyak, tetap berutang, agar kaya raya di kemudian hari. Pada era Habibie, Gus Dur, Megawati, masih terpaksa berutang untuk membiayai pemulihan krisis ekonomi. [rif]