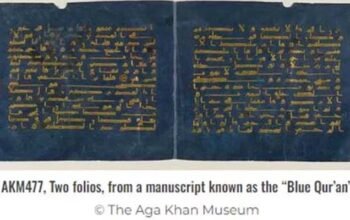“Memang saya sengaja ngaji fikih, kalau ngaji intelektualitas, orang Muhammadiyah juaralah.” ungkap Gus Baha, masih dihadapan para dosen UMM, 14 Juli 2020.
Barisan.co – Gus Baha atau KH Ahmad Bahauddin Nursalim lagi-lagi mengaduk-aduk logika keberagamaan kita. Saya yang besar di lingkungan Muhammadiyah, terus terang kesulitan menangkap kajian fikih yang beliau paparkan. Terlebih beliau bilang: “Fikih itu senam otak.” Sehingga terbayang, betapa berat saya selanjutnya menyimak paparan beliau. Dan, memang demikian kenyataan akhirnya.
“Ada orang yang sarungnya itu pas lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup, tapi kalau nanti rukuk, lututnya agak terbuka. Itu batalnya nunggu rukuk, atau mulai takbir sudah batal?” tanya Gus Baha.
Ada ulama mengatakan: “Ya, batalnya nunggu rukuk. Bagaimanapun terjadinya pembatalan ketika rukuk. Bisa saja juga, ndilalah, sebelum rukuk ada yang menyarungi, sehingga salatnya normal.”
Ulama lain mengatakan: “Mulai awal sudah nggak sah itu salat, karena pasti mengalami batal.”
Gus Baha mencontohkan lagi: “Semisal begini, sekarang bulan ramadan dan kita akan operasi pukul 10 siang. Sehingga kita tahu persis pukul 10 siang besok itu akan divonis medis mesti makan. Nah, malam ini, kamu pilih tetap berniat puasa atau tidak, toh besok pukul 10 harus makan?”
“Kalau kamu orang saleh, pasti akan memilih puasa, karena ini ramadan, meskipun nanti pukul 10 oleh dokter disuruh batal.” kata Gus Baha.
“Setidaknya kita berpikir, kalau kita mati pukul 7 atau pukul 6, paling tidak akan ditulis sebagai orang yang berpuasa. Karena agama itu dimulai dari niat, dari komitmen.”
Gus Baha serasa tak bosan terus mengingatkan pentingnya kearifan dalam mengelola kehidupan. Juga keutamaan berpegang teguh dalam komitmen beragama. Bahwa kebijakan dan kearifan yang utama adalah sesuatu yang tak mendesak jangan dijadikan kebutuhan. Bahwa landasan agama itu komitmen, maka jangan larut oleh kenyataan hidup yang tak ideal.
Kita acap kali sedemikian ribet dalam hidup karena teramat tinggi ekspektasi yang kita bangun. “Sehingga ulama sudah berpendapat ‘ideal iku piye’ (ideal itu bagaimana)?” ujar kiai muda, putra Kiai Nursalim itu.
Betapa kita kerap terlampau berlebihan dan menginginkan banyak hal yang sebetulnya tak diperlukan. Kita pengin makan enak, contohnya. Resep agama itu sederhana, yaitu lapar. Namun, kita latah mengartikan makan enak tatkala makan sate, makan gule, soto, bakso, dan seterusnya. Tempatnya pun harus bagus, di tengah kota, dan sebagainya. Sehingga betapa ribet hidup ini sekira gambaran-gambaran ideal yang kita agungkan.
“Kenapa kok sampai ada garis keras, ya, karena beragama dimulai dari keinginan ideal. Itulah kelirunya. Padahal, sekali lagi, agama itu dimulai dari komitmen, dari niat.” tandas Gus Baha.
Kembali ke soal fikih, Gus Baha membeberkan bahwa dari dulu perbedaan dan perdebatan itu hal biasa. Imam Malik punya murid Imam Syafi’i. Beliau-beliau itu berbeda dalam banyak hal. Contoh begini, tatkala mereka menanggapi kasus: Nabi saw menghukum berat, yaitu harus memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut, kepada seseorang yang sengaja berhubungan suami-istri di siang hari pada bulan Ramadan.
Imam Malik berpikir: pasangan suami-istri yang berhubungan intim itu adalah sesuatu yang boleh, tidak haram. Oleh karenanya, semestinya tidak hanya soal hubungan intim yang dihukumi berat. Semestinya berlaku sama atas segala yang boleh tapi terlarang pada saat Ramadan. Misal, siang hari di saat berpuasa ramadan, kita sengaja makan, sepatutnya juga mendapat sanksi berat untuk memerdekakan budak, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagaimana yang berlaku pada kesengajaan berhubungan suami-istri.